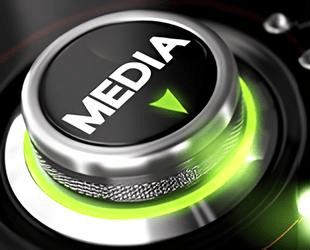Di sebuah subuh yang hening di kaki Gunung Ciremai, seorang pria bersarung dan berikat kepala sedang berbenah rumah panggungnya. Ia bukan petani, bukan juga petugas kebersihan. Ia Dedi Mulyadi — seorang mantan bupati, anggota DPR, dan pemimpin yang menolak meninggalkan akarnya. Di tempat lain, di sudut Jakarta yang hiruk pikuk, seorang intelektual sedang merampungkan catatan kebijakan tentang distribusi keadilan sosial. Ia adalah Anies Baswedan — mantan menteri, mantan gubernur, dan perintis mimpi perubahan lewat kekuatan gagasan.
Mereka berbeda. Sangat berbeda. Tapi hari ini, keduanya berjalan dalam narasi yang sama: menyulam harapan bangsa di tengah demokrasi yang kelelahan.
Dedi Mulyadi lahir dari rahim rakyat biasa. Ia tidak berbicara tentang indeks pembangunan manusia, tapi tentang sumur kering dan anak-anak sekolah yang bertelanjang kaki. Dalam setiap langkahnya, ada jejak kearifan lokal yang disematkan sebagai bentuk perlawanan terhadap politik yang kehilangan hati.
Ia tidak butuh panggung besar. Ia berjalan di pasar, menumpang pikiran rakyat yang sedang mengaduk bubur kacang hijau. Ia mendengarkan dengan tubuh, bukan hanya telinga. Politik bagi Dedi bukan alat kekuasaan, tapi cara untuk menghapus jarak antara penguasa dan yang dikuasai.
“Kalau saya masih bisa dengar suara jangkrik dan peluh petani, berarti saya belum kehilangan arah,” katanya.
Dedi adalah wajah dari demokrasi yang bersahaja. Ia memihak yang kecil, bukan karena pencitraan, tapi karena ia pernah kecil.
Anies Baswedan adalah sosok yang merangkai republik lewat diksi dan data. Ia datang dari dunia akademik, menyelam ke pusaran birokrasi, tapi tak pernah melepas identitas sebagai pemikir. Gagasannya tidak lahir dari empati saja, tapi juga dari riset dan refleksi panjang.
Ia membangun Jakarta tidak sekadar dengan beton, tapi dengan kolaborasi dan nilai. Ia tidak sekadar mengatur kota, tapi membayangkan masa depan bangsa lewat apa yang disebutnya “keadilan ruang dan kesempatan”. Baginya, Indonesia tidak hanya butuh pembangunan, tapi juga peradaban.
“Pemimpin bukan hanya yang menjawab tuntutan hari ini, tapi yang mengantisipasi pertanyaan esok hari,” ucapnya.
Anies adalah wajah dari demokrasi yang berpikir jauh ke depan. Ia berbicara dalam bahasa mimpi, tapi berdiri di tanah realitas.
Dedi dan Anies. Dua nama yang seperti tak serupa, tapi satu dalam kehendak: membawa bangsa ini pulang ke rumahnya. Rumah yang bernama keadilan, kebersamaan, dan keberpihakan.
Dalam dunia yang gaduh oleh polarisasi dan politik transaksional, keduanya menghadirkan oase. Yang satu mengajarkan bahwa mencintai negeri ini dimulai dari menyapu halaman rakyat, yang satu lagi mengingatkan bahwa perubahan tak akan lahir tanpa konsep dan visi.
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar tokoh. Ia butuh narasi. Ia butuh jiwa. Dan dalam keduanya — Dedi dan Anies — bangsa ini melihat pantulan masa depan yang tidak hanya layak diharapkan, tapi juga diperjuangkan.
Kepada generasi muda, tulisan ini bukan sekadar tentang dua orang. Ini tentang arah. Tentang pilihan. Tentang keberanian menolak pragmatisme demi harapan yang lebih besar. Demokrasi bukan sekadar pemilu, tapi perjalanan panjang mencari makna bernegara.
Dedi berjalan dari kampung ke kampung. Anies berjalan dari gagasan ke gagasan. Tapi mereka sama-sama sedang menyalakan pelita — agar anak negeri ini tak lagi berjalan dalam gelap.
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya butuh pembangunan. Ia butuh jiwa.
Dan jiwa itulah yang sedang mereka pertaruhkan, dalam sunyi maupun sorak.
Rubrik: Narasi Bangsa | Edisi I BeritaIndonesia.news