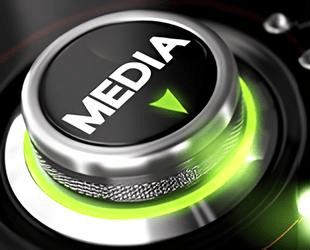Jakarta,- Pernyataan sejumlah analis yang menyebut kabinet perlu “dirijen” agar tak gaduh kembali muncul setelah polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait data subsidi LPG 3 kilogram. Mereka menilai, perbedaan pandangan di ruang publik mencerminkan lemahnya koordinasi, dan menganggap “dirijen” sebagai solusi mutlak.
Namun, benarkah harmoni dalam kabinet hanya bisa lahir dari satu komando yang seragam?
Atau justru, “harmoni” seperti itu sering kali menjadi topeng bagi kolusi dan manipulasi?
Demokrasi Tidak Membutuhkan Keheningan Buatan
Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan bukan tanda kelemahan — melainkan indikasi bahwa proses berpikir dan kontrol internal berjalan.
Kabinet yang setiap menterinya hanya menunggu aba-aba dari “dirijen” bisa terlihat rapi di luar, tetapi sering menyembunyikan banyak kompromi politik di dalam.
Justru, keributan yang lahir dari perdebatan berbasis data jauh lebih sehat dibanding diamnya sistem yang penuh manipulasi di balik layar.
Publik punya hak tahu ketika pejabat negara berbeda pendapat, agar mereka dapat menilai siapa yang paling rasional, siapa yang paling transparan, dan siapa yang sekadar membela kepentingan sektoral.
“Dirijen” Bukan Jaminan Tata Kelola, Bisa Jadi Alat Kontrol
Konsep “dirijen kabinet” sering terdengar manis — seolah menata orkestra agar suara pemerintahan tidak sumbang.
Tetapi dalam praktik politik Indonesia, “dirijen” sering berubah fungsi menjadi alat kontrol politik, bukan alat koordinasi.
Mereka yang berbeda pendapat dicap pembangkang, data yang tidak sejalan dianggap gangguan, dan perdebatan publik dimatikan atas nama “konsolidasi”.
Padahal, tugas utama pemerintahan bukan menjaga keseragaman nada, melainkan menjaga kebenaran data dan ketepatan kebijakan.
Jika semua menteri hanya berbicara dengan bahasa yang sama, publik kehilangan mekanisme alami untuk menguji keputusan negara.
Transparansi Lebih Baik dari Keseragaman
Kasus Purbaya vs Bahlil adalah contoh klasik bagaimana perdebatan publik bisa membuka ruang transparansi.
Publik jadi tahu berapa sebenarnya harga LPG tanpa subsidi, dan sejauh mana beban fiskal yang ditanggung negara.
Apakah data itu sempurna? Tidak selalu. Tapi membuka perdebatan di ruang publik jauh lebih jujur dibanding menutupinya dalam rapat terbatas yang tak pernah diketahui masyarakat.
Kita terlalu lama mengira “harmoni” adalah tanda kekompakan, padahal bisa saja itu hasil represi birokrasi dan politik dagang sapi.
Kabinet yang gaduh tapi transparan lebih mudah diperbaiki daripada kabinet yang tenang tapi busuk dari dalam.
Pemerintahan Butuh Koordinasi, Bukan Keseragaman Pikiran
Koordinasi bukan berarti semua harus sepakat; koordinasi berarti ada mekanisme untuk mengelola perbedaan secara rasional.
Presiden cukup menjadi penentu arah besar, bukan “dirijen” yang memaksa setiap menteri bermain nada yang sama meski datanya berbeda.
Justru, jika menteri berani mengoreksi menteri lain secara terbuka, itu menandakan adanya keberanian politik dan kematangan institusional.
Indonesia tidak membutuhkan kabinet yang sunyi di depan kamera tapi gaduh di belakang meja.
Yang dibutuhkan adalah kabinet yang berani berpikir keras, berdebat di ruang terang, dan mengakui kesalahan tanpa rasa takut.
Karena sejarah menunjukkan:
Kabinet yang terlalu “harmonis” sering kali hanya sedang menyembunyikan ketidakbenaran bersama.